THE LUCKY MAN
"SATU MILYAR!"
Pernah berpikir menjadi pahlawan super? Apa yang kalian pikirkan tentang pahlawan super? Mungkin sebagian berpikir tentang manusia yang bisa terbang, mempunyai tenaga yang sangat kuat atau yang bisa berlari dengan sangat cepat. Dan mungkin sebagian lagi berpikir tentang manusia yang sangat baik hatinya, suka menolong sesama dengan tulus dan bisa membawa kebahagiaan pada orang lain.
Namun, bagaimana dengan keberuntungan? Apa itu juga termasuk sebagai kekuatan super?
Namaku Azam. Waktu itu usiaku 17 tahun. Aku duduk di bangku kelas 3 SMA. Aku seperti remaja kebanyakan, tidak ada yang spesial tentangku. Belum ada yang spesial sampai suatu hari semua cerita berbelok tajam.
Saat itu, guru Bahasa Indonesia-ku, Bu Ida, memberikan tugas untuk mewawancarai seseorang. Tugas ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari lima orang. Aku bersama Yogi, Bunga, Nanda dan Risma satu kelompok. Kami ditugaskan untuk mewawancari seorang penjual tempe keliling. Kami sempat mengeluh keberatan tentang tugas yang kami terima, karena sekarang ini sudah jarang penjual tempe keliling. Kebanyakan penjual tempe saat ini sudah ada lapak di pasar, berjualan di pasar.
Tetapi, Bu Ida tidak menanggapi keluhan kami, dia tetap pada pendiriannya. Katanya, di situlah tantangannya. Dengan jarangnya penjual tempe keliling, semangat dalam mengerjakan tugas kami akan terlihat. Katanya juga, kami akan memperoleh pelajaran hidup yang berarti dari seorang penjual tempe keliling. Baiklah, kami patuh.
Jadilah kami keesokan harinya, yang kebetulan hari Sabtu—sekolah libur pada hari Sabtu, setelah sarapan, membuat janji berkumpul di depan gerbang sekolah untuk mencari dan kemudian mewawancarai seorang penjual tempe.
Setelah lima jam mencari, setelah belasan kali naik turun angkot, setelah bertanya kesana-kemari, setelah mencari sampai ke pinggir kota, melewati gang-gang sempit dan becek, kami belum juga menemukan tukang tempe keliling. Kami memutuskan istirahat, makan siang.
Saat itulah, saat kami baru saja selesai makan di salah satu warung makan, seseorang berteriak di belakang kami.
"Tempe.. tempe..."
Dengan sigap kami menoleh hampir bersamaan.
"Pak, beli tempe, Pak!" Setelah memastikan, aku berteriak.
Penjual tempe itu berhenti di persimpangan. Dia seorang laki-laki, usianya sekitar enam puluhan. Wajahnya penuh dengan keriput, kulitnya coklat gelap, rambutnya sudah memutih, bajunya compang-camping seadanya, dia menggunakan sepeda untuk keliling berjualan tempe. Terdapat dua kaleng besar di sisi kanan dan kiri sepedanya, berisi barang dagangannya, tempe.
"Beli berapa, Nak?" Tanya Bapak itu setelah mengatur posisi sepedanya.
"Satu potong ini harganya berapa, Pak?" Tanyaku. Teman-temanku sudah berada persis di belakangku. Sempat bertanya untuk apa aku membeli tempe, tetapi tidak aku jawab.
"Tiga ribu, Nak."
"Ini uangnya, Pak. Ambil saja kembaliannya." Aku memberi uang nominal lima ribu, kemudian mengambil tempe yang diberikan Bapak itu.
"Terima kasih. Semoga kebaikanmu dibalas dengan kebaikan, Nak." Dia tersenyum.
"Bapak mau lanjut berkeliling?" Tanyaku refleks, karena teringat tujuan kami sebenarnya bukan untuk membeli tempe.
"Tidak, Nak. Bapak ingin pulang ke rumah. Istri Bapak sedang sakit. Bapak janji dengannya untuk makan siang bersama di rumah."
"Rumah Bapak dimana?" Tanyaku.
"Tidak jauh dari sini. Kenapa?"
"Begini, Pak," Sekarang Bunga yang menjelaskan. "Sebenarnya kami dapat tugas sekolah untuk mewawancari seorang penjual tempe keliling. Dan kebetulan kami bertemu dengan Bapak. Apa boleh kami meminta waktu Bapak sebentar?"
"Tentu, Nak. Kalau kalian mau, bisa ikut Bapak ke rumah, karena tidak mungkin Bapak menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian di jalan seperti ini. Kebetulan, sudah lama gubuk tua kami tidak kedatangan tamu. Akan sangat menyenangkan menerima tamu anak-anak pintar seperti kalian. Mari!" Bapak itu tersenyum ramah, kemudian mendorong sepedanya di depan kami.
Tidak jauh dari persimpangan tadi, setelah melewati beberapa belokan, kami sampai di rumah Bapak penjual tempe itu. Rumahnya terletak di ujung gang sempit. Tidak ada jendela, dinding hanya berupa batu bata, atap terlihat banyak yang berlubang, dan lantai hanya beralaskan tikar anyaman. Tetapi, rumah itu bersih, barang-barang tertata dengan rapi, tidak terlihat noda, kotoran, atau debu di manapun.
"Mari masuk! Maaf gubuk kami sempit, berantakan dan sangat tidak nyaman."
Rumah Bapak penjual tempe itu hanya terdapat tiga ruangan. Ruang pertama ruang tamu yang merangkap sebagai kamar tidur. Dan di ruang kedua digunakan sebagai dapur dan terdapat satu kamar mandi.
"Silakan. Tidak usah sungkan, maaf hanya bisa menyediakan ini." Bapak itu baru saja dari dapur, mengambil sepiring penuh tempe goreng dan beberapa gelas berisi air, yang kemudian memberikannya kepada kami.
"Tidak apa, Pak. Maaf merepotkan." Kataku.
"Ini istri Bapak, namanya Sudarsini, kalian bisa panggil Ibu Sudarsi." Bapak itu membantu istrinya yang sejak tadi berbaring untuk duduk. "Ini anak-anak yang penasaran dengan kehidupan sederhana kita, sayang."
Ibu Sudarsi tersenyum kepada kami. Sepertinya usia Ibu Sudarsi tidak berbeda jauh dengan Bapak penjual tempe itu. Wajahnya penuh keriput, rambutnya sudah memutih, kulitnya sawo matang. Dia mengenakan pakaian hangat layaknya orang yang sedang sakit.
"Bapak sendiri namanya siapa?" Tanya Yogi.
"Ah, nama Bapak Qomar."
"Jadi, kalian ingin mewawancarai suami Ibu, ya?" Tanya Ibu Sudarsi. Wajahnya tidak lepas dari senyum. Sangat menyejukan.
"Kalau boleh, Bu." Risma yang menjawab.
"Silakan. Ambilah pelajaran dari orang tua ini, Nak.
Mulailah wawancara kami setelah masing-masing dari kami memperkenalkan diri kepada Bapak Qomar dan Ibu Sudarsi. Aku, Bunga dan Yogi yang melemparkan pertanyaan, sedangkan Nanda mencatat hal penting dan Risma yang merekam pembicaraan menggunakan handphone-nya.
"Bapak sudah lama berjualan tempe keliling?" Tanyaku.
"Sudah, Nak." Pak Qomar membelai rambut istrinya. "Dulu, Bapak tidak menggunakan sepeda. Tetapi, setelah cukup lama menabung, Bapak bisa membeli sepeda. Sudah kurang lebih dua puluh tiga tahun Bapak berjualan tempe keliling."
"Berapa usia Bapak sekarang?" Tanya Yogi.
"Tidak terlampau jauh dengan kalian, kok." Pak Qomar tertawa pelan. "Usia Bapak sekarang 67 tahun."
"Bapak tinggal di rumah ini hanya berdua saja dengan Bu Sudarsi?" Tanya Bunga.
"Iya." Pak Qomar tersenyum lembut. "Hampir 40 tahun kami menikah, tetapi Tuhan belum mempercayakan kepada kami untuk memiliki keturunan. Mungkin menurut Tuhan kami belum siap dan belum pantas."
Satu ruangan lengang, kami merasa iba melihat kondisi Pak Qomar dan Bu Sudarsi. Kemudian pertanyaan dilanjutkan. Pak Qomar seperti mengerti kami. Ditanya satu, dijawab dua. Kadang dia juga asik bercerita, sambil sesekali membelai lembut rambut istrinya. Sampai kami di akhir pertanyaan.
"Apa yang Bapak inginkan setelah ini? Apa Bapak mempunyai impian?" Tanyaku.
"Tentu." Pak Qomar menatap langit-langit ruangan, kemudian menyapu wajah kami, tersenyum. "Kami ingin sekali mendirikan sebuah panti asuhan. Tidak usah besar, yang penting cukup untuk tempat istirahat anak-anak jalanan, yang tidak mempunyai rumah, yang tinggal di kolong jembatan, yang tidak sempat merasakan asiknya bangku sekolah. Kami merasa kasihan kepada mereka. Dengan bersama mereka juga kami seperti keluarga lengkap."
"Dan juga mendirikan sekolah." Bu Sudarsi ikut menjawab. "Jangan lupakan itu, sayang."
Lengang sejenak. Kami merasa kagum melihat pasangan ini. Tetap romantis meski sudah tidak muda lagi, selalu bersyukur apapun keadaannya, selalu merasa cukup, suka berbagi dan hatinya sangat mulia.
Tidak lama, setelah makan satu-dua tempe goreng dan menghabiskan minum yang disediakan, kami pamit.
"Aku jadi ingin membantu Pak Qomar dan Bu Sudarsi." Di dalam angkot, Aku membuka percakapan.
"Tapi bagaimana?" Tanya Yogi.
"Kita kumpulkan uang saja." Usul Nanda.
"Aku ingin membantu mereka mendirikan sekolah dan panti asuhan." Kataku.
"Tidak mungkin kita punya uang sebanyak itu." Risma menggeleng pelan.
Tiba-tiba aku teringat sesuatu. "Kalian tahu acara di televisi yang mencoba peruntungan dan berhadiahkan uang satu milyar itu?"
Teman-temanku mengangguk.
"Aku akan mencoba peruntunganku di acara itu."
Awalnya teman-temaku ragu, tidak setuju. Tetapi itu keputusanku, dan aku akan ikut acara itu.
Ketika tiba di rumah, aku langsung menceritakan kejadian tadi siang kepada kedua orang tuaku, dan juga niatanku untuk mengikuti acara televisi itu. Berbeda dengan teman-temanku, kedua orang tuaku menyetujui tanpa ragu, dan setelah makan malam aku mengirim e-mail pada acara tersebut, mendaftar. Tidak lama, e-mailku dibalas. Dan aku akan mengikuti acara itu minggu depan.
Minggu depannya, setelah sarapan, aku menuju studio televisi itu, ditemani Ayah, Mama dan teman-temanku.
Acara itu dibagi menjadi tiga sesi. Pertama, memutar "roda nasib".
Setelah pembawa acara membuka acara, dia memintaku untuk memutar "roda nasib".
"Ayo, Azam. Silakan diputar!"
Pada "roda nasib" terdapat lima permainan pada sesi ke dua. Roda yang aku putar berhenti pada permainan memilih kotak.
Tetapi, pembawa acara memintaku agar memilih untuk lanjut ke permainan ke dua atau menerima uang nominal seratus juta. Permainan baru dimulai, lagipula, seratus juta belum cukup. Aku memilih lanjut bermain.
Permainan kedua, "kotak nasib",
Pembawa acara memberitahu bahwa terdapat dua puluh tiga kotak berisi nominal uang. Dari mulai sepuluh ribu, sampai lima ratus juta. Tetapi, ada satu kotak yang tidak berisi nominal uang. Kotak yang akan membawaku pada permainan ketiga.
Kesempatan pertama, aku memilih kotak nomor lima. Kotak itu berisi nominal uang empat ratus sepuluh juta. Aku kaget, penonton juga kaget. Tetapi itu belum cukup, aku harus mendapatkan hadiah terbesar!
Kesempatan kedua, aku memilih kotak nomor tiga belas. Kotak itu berisi nominal uang dua ratus lima puluh juta. Aku bingung. Jika aku memilih kesempatan ketiga dan ternyata nominalnya kecil, tidak akan cukup. Aku meminta saran kepada orang tua dan teman-temanku. Semua memberi usul agar aku mengambil kotak itu. Tetapi, dua ratus lima puluh juta belum cukup.
Kesempatan ketiga, aku memilih kotak nomor dua puluh tiga. Satu ruangan tegang, dan ternyata kotak itu berisi tiket untuk aku bisa melanjutkan ke permainan ke tiga.
Permainan ke tiga adalah permainan "tawar-menawar atau tetap mengadu nasib".
Aku ditawarkan uang sebesar tujuh ratus juta. Namun sudah kepalang tanggung. Aku sudah sejauh ini. Aku memilih mengadu nasib dengan memutar "roda nasib emas". Sama seperti roda nasib di permainan pertama, bedanya isi "roda nasib emas" ini berada di belakang roda, tidak diketahui. Ada sepuluh "nasib", tiga di antaranya zonk, tidak bernilai sama sekali, dan salah satunya ada nominal hadiah terbesar, satu milyar.
Pembawa acara tidak menyerah memberikan tawaran kepadaku sampai nominal delapan ratus lima belas juta. Aku? Aku tetap pada pendirianku, memutar "roda nasib emas."
Aku putar. Beberapa detik kemudian roda tersebut berhenti. Pembawa acara mengambil secarik kertas dari balik roda. Kertasnya berwarna emas! Itu artinya hadiah terbesar, satu milyar!
Satu studio bersorak, ramai riuh. Pembawa acara menyalamiku, memberi selamat. Aku juga tidak menyangka bahwa aku akan mendapat hadiah terbesar. Pembawa acara memberiku julukan sebagai "The Lucky-Man".
Aku sangat bersyukur. Seminggu kemudian aku menuju rumah Pak Qomar dan Bu Sudarsi, memberikan kabar bahagia pada mereka. Tak henti-hentinya mereka mengucap syukur dan terima kasih.
Apa keberuntungan bisa dibilang sebagai kekuatan super?
TAMAT
Pernah berpikir menjadi pahlawan super? Apa yang kalian pikirkan tentang pahlawan super? Mungkin sebagian berpikir tentang manusia yang bisa terbang, mempunyai tenaga yang sangat kuat atau yang bisa berlari dengan sangat cepat. Dan mungkin sebagian lagi berpikir tentang manusia yang sangat baik hatinya, suka menolong sesama dengan tulus dan bisa membawa kebahagiaan pada orang lain.
Namun, bagaimana dengan keberuntungan? Apa itu juga termasuk sebagai kekuatan super?
Namaku Azam. Waktu itu usiaku 17 tahun. Aku duduk di bangku kelas 3 SMA. Aku seperti remaja kebanyakan, tidak ada yang spesial tentangku. Belum ada yang spesial sampai suatu hari semua cerita berbelok tajam.
Saat itu, guru Bahasa Indonesia-ku, Bu Ida, memberikan tugas untuk mewawancarai seseorang. Tugas ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari lima orang. Aku bersama Yogi, Bunga, Nanda dan Risma satu kelompok. Kami ditugaskan untuk mewawancari seorang penjual tempe keliling. Kami sempat mengeluh keberatan tentang tugas yang kami terima, karena sekarang ini sudah jarang penjual tempe keliling. Kebanyakan penjual tempe saat ini sudah ada lapak di pasar, berjualan di pasar.
Tetapi, Bu Ida tidak menanggapi keluhan kami, dia tetap pada pendiriannya. Katanya, di situlah tantangannya. Dengan jarangnya penjual tempe keliling, semangat dalam mengerjakan tugas kami akan terlihat. Katanya juga, kami akan memperoleh pelajaran hidup yang berarti dari seorang penjual tempe keliling. Baiklah, kami patuh.
Jadilah kami keesokan harinya, yang kebetulan hari Sabtu—sekolah libur pada hari Sabtu, setelah sarapan, membuat janji berkumpul di depan gerbang sekolah untuk mencari dan kemudian mewawancarai seorang penjual tempe.
Setelah lima jam mencari, setelah belasan kali naik turun angkot, setelah bertanya kesana-kemari, setelah mencari sampai ke pinggir kota, melewati gang-gang sempit dan becek, kami belum juga menemukan tukang tempe keliling. Kami memutuskan istirahat, makan siang.
Saat itulah, saat kami baru saja selesai makan di salah satu warung makan, seseorang berteriak di belakang kami.
"Tempe.. tempe..."
Dengan sigap kami menoleh hampir bersamaan.
"Pak, beli tempe, Pak!" Setelah memastikan, aku berteriak.
Penjual tempe itu berhenti di persimpangan. Dia seorang laki-laki, usianya sekitar enam puluhan. Wajahnya penuh dengan keriput, kulitnya coklat gelap, rambutnya sudah memutih, bajunya compang-camping seadanya, dia menggunakan sepeda untuk keliling berjualan tempe. Terdapat dua kaleng besar di sisi kanan dan kiri sepedanya, berisi barang dagangannya, tempe.
"Beli berapa, Nak?" Tanya Bapak itu setelah mengatur posisi sepedanya.
"Satu potong ini harganya berapa, Pak?" Tanyaku. Teman-temanku sudah berada persis di belakangku. Sempat bertanya untuk apa aku membeli tempe, tetapi tidak aku jawab.
"Tiga ribu, Nak."
"Ini uangnya, Pak. Ambil saja kembaliannya." Aku memberi uang nominal lima ribu, kemudian mengambil tempe yang diberikan Bapak itu.
"Terima kasih. Semoga kebaikanmu dibalas dengan kebaikan, Nak." Dia tersenyum.
"Bapak mau lanjut berkeliling?" Tanyaku refleks, karena teringat tujuan kami sebenarnya bukan untuk membeli tempe.
"Tidak, Nak. Bapak ingin pulang ke rumah. Istri Bapak sedang sakit. Bapak janji dengannya untuk makan siang bersama di rumah."
"Rumah Bapak dimana?" Tanyaku.
"Tidak jauh dari sini. Kenapa?"
"Begini, Pak," Sekarang Bunga yang menjelaskan. "Sebenarnya kami dapat tugas sekolah untuk mewawancari seorang penjual tempe keliling. Dan kebetulan kami bertemu dengan Bapak. Apa boleh kami meminta waktu Bapak sebentar?"
"Tentu, Nak. Kalau kalian mau, bisa ikut Bapak ke rumah, karena tidak mungkin Bapak menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian di jalan seperti ini. Kebetulan, sudah lama gubuk tua kami tidak kedatangan tamu. Akan sangat menyenangkan menerima tamu anak-anak pintar seperti kalian. Mari!" Bapak itu tersenyum ramah, kemudian mendorong sepedanya di depan kami.
Tidak jauh dari persimpangan tadi, setelah melewati beberapa belokan, kami sampai di rumah Bapak penjual tempe itu. Rumahnya terletak di ujung gang sempit. Tidak ada jendela, dinding hanya berupa batu bata, atap terlihat banyak yang berlubang, dan lantai hanya beralaskan tikar anyaman. Tetapi, rumah itu bersih, barang-barang tertata dengan rapi, tidak terlihat noda, kotoran, atau debu di manapun.
"Mari masuk! Maaf gubuk kami sempit, berantakan dan sangat tidak nyaman."
Rumah Bapak penjual tempe itu hanya terdapat tiga ruangan. Ruang pertama ruang tamu yang merangkap sebagai kamar tidur. Dan di ruang kedua digunakan sebagai dapur dan terdapat satu kamar mandi.
"Silakan. Tidak usah sungkan, maaf hanya bisa menyediakan ini." Bapak itu baru saja dari dapur, mengambil sepiring penuh tempe goreng dan beberapa gelas berisi air, yang kemudian memberikannya kepada kami.
"Tidak apa, Pak. Maaf merepotkan." Kataku.
"Ini istri Bapak, namanya Sudarsini, kalian bisa panggil Ibu Sudarsi." Bapak itu membantu istrinya yang sejak tadi berbaring untuk duduk. "Ini anak-anak yang penasaran dengan kehidupan sederhana kita, sayang."
Ibu Sudarsi tersenyum kepada kami. Sepertinya usia Ibu Sudarsi tidak berbeda jauh dengan Bapak penjual tempe itu. Wajahnya penuh keriput, rambutnya sudah memutih, kulitnya sawo matang. Dia mengenakan pakaian hangat layaknya orang yang sedang sakit.
"Bapak sendiri namanya siapa?" Tanya Yogi.
"Ah, nama Bapak Qomar."
"Jadi, kalian ingin mewawancarai suami Ibu, ya?" Tanya Ibu Sudarsi. Wajahnya tidak lepas dari senyum. Sangat menyejukan.
"Kalau boleh, Bu." Risma yang menjawab.
"Silakan. Ambilah pelajaran dari orang tua ini, Nak.
Mulailah wawancara kami setelah masing-masing dari kami memperkenalkan diri kepada Bapak Qomar dan Ibu Sudarsi. Aku, Bunga dan Yogi yang melemparkan pertanyaan, sedangkan Nanda mencatat hal penting dan Risma yang merekam pembicaraan menggunakan handphone-nya.
"Bapak sudah lama berjualan tempe keliling?" Tanyaku.
"Sudah, Nak." Pak Qomar membelai rambut istrinya. "Dulu, Bapak tidak menggunakan sepeda. Tetapi, setelah cukup lama menabung, Bapak bisa membeli sepeda. Sudah kurang lebih dua puluh tiga tahun Bapak berjualan tempe keliling."
"Berapa usia Bapak sekarang?" Tanya Yogi.
"Tidak terlampau jauh dengan kalian, kok." Pak Qomar tertawa pelan. "Usia Bapak sekarang 67 tahun."
"Bapak tinggal di rumah ini hanya berdua saja dengan Bu Sudarsi?" Tanya Bunga.
"Iya." Pak Qomar tersenyum lembut. "Hampir 40 tahun kami menikah, tetapi Tuhan belum mempercayakan kepada kami untuk memiliki keturunan. Mungkin menurut Tuhan kami belum siap dan belum pantas."
Satu ruangan lengang, kami merasa iba melihat kondisi Pak Qomar dan Bu Sudarsi. Kemudian pertanyaan dilanjutkan. Pak Qomar seperti mengerti kami. Ditanya satu, dijawab dua. Kadang dia juga asik bercerita, sambil sesekali membelai lembut rambut istrinya. Sampai kami di akhir pertanyaan.
"Apa yang Bapak inginkan setelah ini? Apa Bapak mempunyai impian?" Tanyaku.
"Tentu." Pak Qomar menatap langit-langit ruangan, kemudian menyapu wajah kami, tersenyum. "Kami ingin sekali mendirikan sebuah panti asuhan. Tidak usah besar, yang penting cukup untuk tempat istirahat anak-anak jalanan, yang tidak mempunyai rumah, yang tinggal di kolong jembatan, yang tidak sempat merasakan asiknya bangku sekolah. Kami merasa kasihan kepada mereka. Dengan bersama mereka juga kami seperti keluarga lengkap."
"Dan juga mendirikan sekolah." Bu Sudarsi ikut menjawab. "Jangan lupakan itu, sayang."
Lengang sejenak. Kami merasa kagum melihat pasangan ini. Tetap romantis meski sudah tidak muda lagi, selalu bersyukur apapun keadaannya, selalu merasa cukup, suka berbagi dan hatinya sangat mulia.
Tidak lama, setelah makan satu-dua tempe goreng dan menghabiskan minum yang disediakan, kami pamit.
"Aku jadi ingin membantu Pak Qomar dan Bu Sudarsi." Di dalam angkot, Aku membuka percakapan.
"Tapi bagaimana?" Tanya Yogi.
"Kita kumpulkan uang saja." Usul Nanda.
"Aku ingin membantu mereka mendirikan sekolah dan panti asuhan." Kataku.
"Tidak mungkin kita punya uang sebanyak itu." Risma menggeleng pelan.
Tiba-tiba aku teringat sesuatu. "Kalian tahu acara di televisi yang mencoba peruntungan dan berhadiahkan uang satu milyar itu?"
Teman-temanku mengangguk.
"Aku akan mencoba peruntunganku di acara itu."
Awalnya teman-temaku ragu, tidak setuju. Tetapi itu keputusanku, dan aku akan ikut acara itu.
Ketika tiba di rumah, aku langsung menceritakan kejadian tadi siang kepada kedua orang tuaku, dan juga niatanku untuk mengikuti acara televisi itu. Berbeda dengan teman-temanku, kedua orang tuaku menyetujui tanpa ragu, dan setelah makan malam aku mengirim e-mail pada acara tersebut, mendaftar. Tidak lama, e-mailku dibalas. Dan aku akan mengikuti acara itu minggu depan.
Minggu depannya, setelah sarapan, aku menuju studio televisi itu, ditemani Ayah, Mama dan teman-temanku.
Acara itu dibagi menjadi tiga sesi. Pertama, memutar "roda nasib".
Setelah pembawa acara membuka acara, dia memintaku untuk memutar "roda nasib".
"Ayo, Azam. Silakan diputar!"
Pada "roda nasib" terdapat lima permainan pada sesi ke dua. Roda yang aku putar berhenti pada permainan memilih kotak.
Tetapi, pembawa acara memintaku agar memilih untuk lanjut ke permainan ke dua atau menerima uang nominal seratus juta. Permainan baru dimulai, lagipula, seratus juta belum cukup. Aku memilih lanjut bermain.
Permainan kedua, "kotak nasib",
Pembawa acara memberitahu bahwa terdapat dua puluh tiga kotak berisi nominal uang. Dari mulai sepuluh ribu, sampai lima ratus juta. Tetapi, ada satu kotak yang tidak berisi nominal uang. Kotak yang akan membawaku pada permainan ketiga.
Kesempatan pertama, aku memilih kotak nomor lima. Kotak itu berisi nominal uang empat ratus sepuluh juta. Aku kaget, penonton juga kaget. Tetapi itu belum cukup, aku harus mendapatkan hadiah terbesar!
Kesempatan kedua, aku memilih kotak nomor tiga belas. Kotak itu berisi nominal uang dua ratus lima puluh juta. Aku bingung. Jika aku memilih kesempatan ketiga dan ternyata nominalnya kecil, tidak akan cukup. Aku meminta saran kepada orang tua dan teman-temanku. Semua memberi usul agar aku mengambil kotak itu. Tetapi, dua ratus lima puluh juta belum cukup.
Kesempatan ketiga, aku memilih kotak nomor dua puluh tiga. Satu ruangan tegang, dan ternyata kotak itu berisi tiket untuk aku bisa melanjutkan ke permainan ke tiga.
Permainan ke tiga adalah permainan "tawar-menawar atau tetap mengadu nasib".
Aku ditawarkan uang sebesar tujuh ratus juta. Namun sudah kepalang tanggung. Aku sudah sejauh ini. Aku memilih mengadu nasib dengan memutar "roda nasib emas". Sama seperti roda nasib di permainan pertama, bedanya isi "roda nasib emas" ini berada di belakang roda, tidak diketahui. Ada sepuluh "nasib", tiga di antaranya zonk, tidak bernilai sama sekali, dan salah satunya ada nominal hadiah terbesar, satu milyar.
Pembawa acara tidak menyerah memberikan tawaran kepadaku sampai nominal delapan ratus lima belas juta. Aku? Aku tetap pada pendirianku, memutar "roda nasib emas."
Aku putar. Beberapa detik kemudian roda tersebut berhenti. Pembawa acara mengambil secarik kertas dari balik roda. Kertasnya berwarna emas! Itu artinya hadiah terbesar, satu milyar!
Satu studio bersorak, ramai riuh. Pembawa acara menyalamiku, memberi selamat. Aku juga tidak menyangka bahwa aku akan mendapat hadiah terbesar. Pembawa acara memberiku julukan sebagai "The Lucky-Man".
Aku sangat bersyukur. Seminggu kemudian aku menuju rumah Pak Qomar dan Bu Sudarsi, memberikan kabar bahagia pada mereka. Tak henti-hentinya mereka mengucap syukur dan terima kasih.
Apa keberuntungan bisa dibilang sebagai kekuatan super?
TAMAT

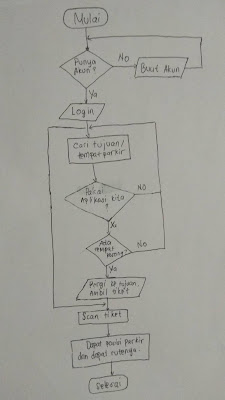

Comments
Post a Comment